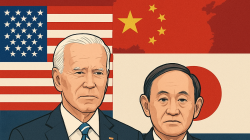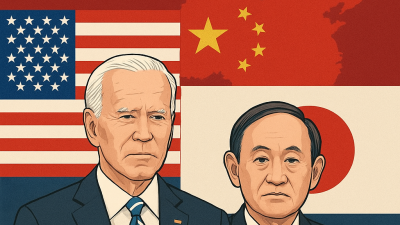Mphnews – Iran tengah berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang protes berskala nasional kembali mengguncang negara tersebut, disebut-sebut sebagai salah satu krisis paling serius sejak Revolusi Islam 1979. Ribuan warga turun ke jalan di lebih dari 100 kota yang tersebar di seluruh 31 provinsi, menandai meluasnya ketidakpuasan publik yang tak lagi terbatas pada pusat-pusat urban seperti Teheran.
Berbeda dengan gelombang demonstrasi sebelumnya, protes kali ini tidak berhenti pada tuntutan reformasi ekonomi. Di banyak titik, massa secara terbuka menyerukan pembubaran Republik Islam dan menyasar langsung pucuk kekuasaan, yakni Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Slogan-slogan keras seperti “matilah diktator” menggema di jalanan, mencerminkan pergeseran signifikan dari kritik kebijakan menuju penolakan sistem politik secara menyeluruh.
Akar krisis ini bersifat multidimensional. Tekanan ekonomi menjadi pemicu utama. Nilai mata uang rial terus terdepresiasi, inflasi melonjak, dan daya beli masyarakat tergerus. Sanksi internasional, khususnya sejak Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir pada 2018, memperparah kondisi sektor minyak yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan negara. Di saat yang sama, Iran menghadapi krisis energi domestik akibat infrastruktur yang menua dan minim investasi.
Masalah lingkungan turut memperkeruh situasi. Kekeringan berkepanjangan dan pengelolaan sumber daya air yang buruk membuat jutaan warga hidup dalam kondisi kelangkaan air. Waduk-waduk utama, termasuk yang memasok Teheran, berada pada level kritis. Tekanan hidup yang kian berat mendorong protes ekonomi berubah menjadi perlawanan sosial dan politik yang lebih luas.
Salah satu aspek paling menonjol dari gelombang protes ini adalah peran perempuan. Sejak aksi besar pada 2022, perempuan Iran konsisten berada di garis depan perlawanan, menentang kebijakan wajib hijab dan kontrol negara atas kehidupan pribadi. Tindakan simbolis seperti melepas atau membakar hijab di ruang publik menjadi lambang perlawanan terhadap fondasi moral Republik Islam.
Di tengah kekacauan, simbol-simbol era pra-1979 kembali bermunculan. Nama Reza Pahlavi, putra syah terakhir Iran, disebut dalam diskursus internasional dan sebagian aksi protes. Namun para analis menilai hal ini lebih mencerminkan krisis legitimasi ideologis rezim ketimbang konsensus untuk mengembalikan monarki.
Meski tekanan meningkat, para pengamat menegaskan bahwa Iran belum berada di ambang runtuhnya negara. Aparat keamanan masih berfungsi dan kapasitas represif rezim tetap signifikan. Namun ketika stabilitas ekonomi dan kontrol keamanan sama-sama tertekan, risiko ketidakstabilan sistemik meningkat tajam. Masa depan Iran kini bergantung pada rangkaian keputusan di jalanan, institusi keamanan, dan pusat kekuasaan—dalam waktu yang relatif singkat namun menentukan.